
Saya tidak sedang merencanakan nostalgia ketika menonton perjalanan seorang vlogger, Nugroho Febianto, yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia. Tapi begitulah ingatan bekerja. Satu potongan cerita orang lain—ekspresi kagum, kekagokan kecil, langkah yang masih ragu—cukup untuk menyeret saya kembali ke satu waktu yang jauh, ke tahun 2014, ketika saya sendiri menjadi seseorang yang benar-benar “baru” dalam dunia perjalanan.
Perjalanan pertama ke Malaysia.
Perjalanan pertama seminggu di luar negara.
Perjalanan yang tidak sepenuhnya saya pahami, namun justru itulah yang membuatnya berkesan.
Secara teori, saat itu memang bukan pertama kalinya Malaysia mencap paspor saya, karena saya sudah mampir ke Johor di tahun sebelumnya. Secara teori, saya juga sebenarnya bersama seorang rekan perjalanan, tapi saya lebih memilih untuk menganggapnya tak ada.
Terminal Larkin dan Makan Tengah Malam yang Magis
Saya memasuki Malaysia lewat jalur darat, via Johor. Saat itu, tujuan saya sesederhana mimpi-mimpi traveler pemula lainnya: Penang. Saya ingin melihat George Town, mural-muralnya, bangunan tuanya, dan mencicipi makanan yang selama ini hanya saya dengar dari cerita orang lain.
Tapi niat sederhana sering kali tidak berjalan sederhana.

Bus langsung ke Penang sudah habis. Saya masih terlalu naif untuk berpikir bahwa “pasti ada bus lain nanti”. Saya belum terbiasa melakukan riset mendalam, belum mengenal platform pemesanan online seperti EasyBook, bahkan belum benar-benar memahami ritme transportasi lintas negara. Yang saya tahu: saya sudah terlanjur masuk Malaysia, dan saya harus melanjutkan perjalanan—entah ke mana.
Di situlah saya mengambil keputusan yang akan terus saya ingat bertahun-tahun kemudian. Saya “ngeteng” ke Kuala Lumpur.
Sebelum bus ke Kuala Lumpur berangkat, saya menunggu di Terminal Larkin, Johor Bahru. Waktu sudah masuk tengah malam. Badan lelah, pikiran campur aduk antara cemas dan penasaran, dan tentu saja—lapar.
Saya membeli makanan seadanya. Tidak ada yang spesial. Bukan makanan yang akan masuk daftar kuliner favorit, bukan juga pengalaman kuliner yang layak difoto. Saya makan sambil duduk, dikelilingi suara pengumuman terminal, deru mesin bus, dan orang-orang yang sebagian tampak ingin cepat sampai tujuan, sebagian lain terlihat sama bingungnya dengan saya.
Tapi justru momen seperti itu yang selalu terasa magis bagi saya.
Tengah malam di terminal punya suasana yang sulit dijelaskan. Waktu seperti berjalan lebih lambat. Dunia terasa lebih sunyi, lebih jujur. Kita sendirian dengan pikiran sendiri. Tidak sedang menjadi siapa-siapa, tidak sedang mengejar apa-apa, selain melanjutkan perjalanan.
Di situlah, tanpa saya sadari, benih kecintaan saya pada perjalanan solo tumbuh. Bukan dari destinasi, bukan dari foto-foto cantik, melainkan dari momen diam—di bangku terminal, dengan makanan hangat dan kepala penuh angan.
Penang dan Excitement yang Tidak Pernah Sama
Bus membawa saya ke Kuala Lumpur. Saya tiba pagi buta di Pudu Sentral. Saat itu, meski Terminal Bersepadu Selatan (TBS) sudah ada, Pudu Sentral masih beroperasi dan menjadi simpul penting bus jarak jauh. Terminal masih tutup, saya datang terlalu cepat.
Saya menunggu.
Duduk diam. Menahan kantuk. Mengamati sekitar. Rasanya aneh berada di kota asing pada jam di mana sebagian besar penghuninya masih tidur. Tidak ada hiruk pikuk, tidak ada landmark megah—hanya bangunan terminal, lampu temaram, dan waktu yang berjalan pelan.
Begitu terminal buka, saya segera membeli tiket bus ke Penang. Rasanya seperti menyelesaikan satu level dalam permainan. Sederhana, tapi memuaskan. Saya masih ingat perasaan lega saat memegang tiket itu—seolah perjalanan ini akhirnya punya arah yang jelas.



Saya tiba di Penang sore hari,, meleset dari rencana yang ingin tiba pagi-pagi. Setelah check-in hostel, mandi, dan menjatuhkan ransel ke sudut ranjang saya di dormitory room, saya keluar berjalan. Tidak ada rencana. Tidak ada target tempat.
Tubuh lelah.
Mata mengantuk.
Tapi hati terasa… ringan.
Kebayang nggak sih? Setelah seharian semalaman dalam perjalanan, pakai jaket dan celana panjang, pakai sepatu, memanggul ransel berat, lepek dan lengket oleh keringat. Lalu, kau selesai mandi dan berjalan leluasa di trotoar kota, dengan hanya kaos oblong, celana pendek, sendal, dan tas slempang. Rasanya begitu… enteng dan segar.
Excitement perjalanan pertama selalu terasa berbeda. Kita belum tahu apa-apa, jadi segalanya terasa baru. Jalanan, aroma, suara, bahkan cara orang berbicara. Kita tidak membandingkan, karena memang belum punya pembanding.
Penang tidak menyambut saya dengan sesuatu yang dramatis. Tidak ada kejadian besar. Tapi justru dari kesederhanaan itulah kenangan itu bertahan. Saya masih bisa mengingat perasaan “akhirnya sampai”, perasaan bahwa dunia ternyata lebih luas dari yang selama ini saya bayangkan.
Jatuh Cinta dengan Kuala Lumpur
Entah esoknya atau lusanya—jujur saya sudah lupa detail waktunya—saya kembali lagi ke Kuala Lumpur, masih dengan bus. Waktu itu, KL bukan sekadar kota transit. Ada sesuatu yang membuat saya ingin kembali, meski belum bisa saya jelaskan.
Dan lagi-lagi, saya tiba pagi-pagi buta di Pudu Sentral.

Kali ini, tujuan saya Bukit Bintang, tempat hostel saya berada. Saya menunggu LRT Ampang / Sri Petaling Line beroperasi. Waktu masih pagi sekali. Kota belum sepenuhnya bangun.
Saat akhirnya tiba di Bukit Bintang, saya duduk di depan sebuah convenience store karena hostel juga belum memperbolehkan check-in. Sarapan kecil. Kopi atau minuman sederhana. Saya melihat warga lokal mulai bergegas—pakaian rapi, langkah cepat, wajah-wajah yang tampak sudah akrab dengan rutinitas kota.
Di momen itulah, tanpa peringatan apa pun, saya jatuh cinta dengan Kuala Lumpur.
KL terasa seperti titik tengah antara Singapura dan Jakarta. Tidak setertib Singapura, tapi juga tidak sepadat Jakarta. Kota yang hidup, tapi tidak melelahkan. Modern, tapi masih memberi ruang untuk bernapas.
Saya menjelajahi kota itu dengan cara paling sederhana: naik kereta.
LRT Ampang Line.
LRT Kelana Jaya Line.
Monorail.
KTM Komuter.
Bahkan KLIA Ekspres—yang mahal, tapi saya bela-belain karena saya ingin tahu rasanya.




Saat itu, MRT belum ada seperti sekarang. Tapi justru keterbatasan itu membuat eksplorasi terasa lebih personal. Saya menghafal rute, memahami ritme stasiun, dan perlahan merasa seperti “pendatang yang mulai mengerti”.
Saya makan dengan lahap. Teh tarik demi teh tarik. Nasi lemak untuk sarapan. Nasi kandar untuk mengisi perut, meski harus siap berkeringat. Saya tidak mencari yang viral. Saya hanya mengikuti insting dan rekomendasi acak. Dan entah kenapa, semuanya terasa pas.
Dari Perjalanan ke Keinginan Tinggal
Bertahun-tahun berlalu sejak perjalanan itu, dunia berubah. Kuala Lumpur berubah. Saya pun berubah. Tapi kenangan perjalanan pertama itu tetap tinggal di kepala—seperti potongan film yang bisa diputar ulang kapan saja.
Hari ini, saya bahkan menyimpan keinginan untuk tinggal di Kuala Lumpur sebagai pekerja sementara. Bukan sekadar berkunjung, tapi hidup. Merasakan kota itu sebagai latar keseharian, bukan hanya destinasi. Mungkin karena KL selalu terasa seperti kota yang memberi saya “ruang”. Ruang untuk jadi asing tanpa merasa terasing.
Tentang Perjalanan, Kamera, dan Waktu yang Akan Datang
Saya belum punya kesempatan lagi untuk melakukan perjalanan solo ke luar negeri. Hidup bergerak ke fase lain—tanggung jawab, pekerjaan, hal-hal yang membuat waktu terasa lebih padat dan berlalu begitu cepat.
Tapi saya tahu satu hal: ketika waktunya tiba, saya ingin kembali bepergian. Dan kali ini, saya ingin mendokumentasikannya dalam bentuk vlog. Bukan untuk pamer destinasi, bukan untuk mengejar algoritma, tapi untuk merekam momen-momen kecil—terminal tengah malam, sarapan sederhana, perjalanan pagi yang sunyi.
Karena justru di situlah perjalanan hidup.

Perjalanan pertama mungkin tidak sempurna. Rutenya berantakan. Keputusannya setengah nekat, tapi dari sanalah semuanya bermula. Dan Malaysia—dengan Terminal Larkin, Pudu Sentral, Bukit Bintang, dan secangkir teh tarik—akan selalu menjadi bagian dari cerita itu. Terima kasih sudah membaca, keep learning by traveling~




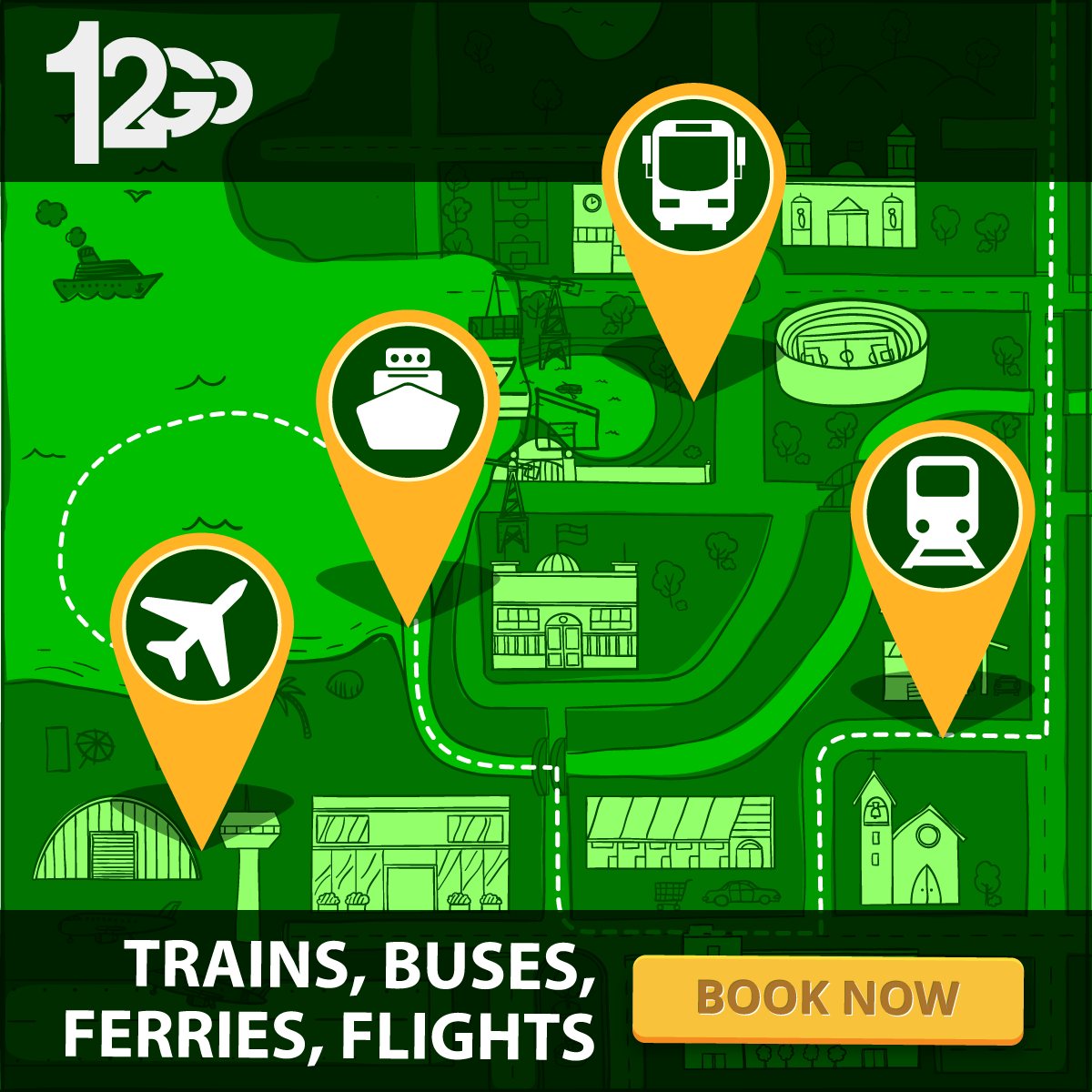









Tak ada target tempat. Saya suka kalimat ini.
Saya dulu malah pernah melakukan, entar malam tidur di mana entah, lalu besok mau ngapain dan ke mana ya embuh.
Alhasil cuti sepuluh hari masih kurang, sehingga saya minta surat dari dokter untuk saya kirim via fax ke kantor Jakarta. Waktu itu internet masih langka, warnet belum musim, dan kantor saya belum pasang internet. Ponsel juga belum lumrah.
mas nugiiiiie, aku merinding baca ini, bukan Krn ga bagus, tp Krn aku paham yg kamu rasain terhadap KL 😍😍😍😍. Itu kenapa aku tidak tahun kesana, antara KL atau Penang. Krn memang senyaman itu, bagai rumah sendiri. Ga usah ditanya ttg impian tinggal di sana. Pengen bangetttttt.dan banyak kali aku doa, semoga Raka bisa dpt kesempatan utk dipindahkan ke CIMB Malaysia. Belum terkabul, tp aku berharap terus. Even aku punya cita2, anak2 ku nanti hrs kuliah di sana. Setidaknya yg ini aku akan usahain banget bisa terwujud. JD ada alasan utk selalu kembali ke Malaysia. KL, Penang atau Ipoh, 3 kota fav ku, yg selalu bikin pikiran tenang. Btw, kangen juga baca tulisanmu yg kayak dulu, traveling backpacking , menikmati destinasi, dan banyak unsur kejutan 😄👍